SIAPA SEBENARYA SOEHARTO ? (PART 5)

Benih Orde Baru tumbuh di atas genangan darah dan tetesan air mata rakyatnya. Arah pembangunan (Repelita) didesain sesuai dengan keinginan Washington dengan mengutamakan eksploitasi segenap kekayaan alam bumi Indonesia yang dikeruk habis-habisan dan diangkut ke luar guna memperkaya negeri-negeri Barat.
Inti pergantian kekuasaan dari Bung Karno ke Jenderal Besar Suharto adalah berubahnya prinsip pembangunan ekonomi Indonesia, dari kemandirian menjadi ketergantungan. April 1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966, Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal: “Go to hell with your aid!”
Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs; Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).
Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.
Mahasiswa melihat penguasa baru ini pun tidak beres. Militer dipelihara dan digunakan sebagai tameng penjaga status-quo. Kekuatan politik rakyat dibabat habis dengan dibonsainya partai-partai politik hingga hanya ada tiga: Golkar, PPP, dan PDI. “Pada Februari 1970, pemerintah mengumumkan semua pegawai negeri harus setia kepada pemerintah. Mereka tidak diizinan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar,” demikian Ricklefs.
Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan Kantor Pangdam Siliwangi dan juga Kantor Gubernur Jawa Barat, 9 Oktober 1970, dengan keras mengecam kelakuan tentara yang kian hari kian dianggap repressif. Delapan tuntutan kala itu disampaikan: Kebalkah ABRI terhadap hukum! Mengapa pakaian seragam diangap lebih mampu? Apakah seragam sama dengan karcis kereta-api, bioskop, bus, opelet? Kapan ABRI berubah kelakuan? Siapa berani tertibkan ABRI? Kapan ada jaminan hukum bagi rakyat? Sudah merdekakah kita dari kesewenang-wenangan hukum?” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des 1985).
Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya. Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono Hoemardhani.”
Suharto memang seorang pemimpin yang sangat lihai, dan tentu saja licin bagai belut yang berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua orang yang berada di sekelilingnya guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang kekuatan militer, teknokrat pro-kapitalisme, dan ormas keagamaan, terutama umat Islam, untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo menjadi sesepuhnya, dan kemudian di era 1980-an akan muncul tokoh sentral Islamophobia, murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.
Dengan dukungan penuh terutama dari militer—tentu ada harga yang harus dibayarkan oleh Suharto, yakni membagi kue KKN kepada para perwiranya—maka kekuatan sipil tidak ada artinya. Siapa pun yang berseberangan dengannya, maka langsung dicap sebagai Anti Pancasila. Selama periode 1970-awal 1980-an, tidak ada kekuatan sipil yang berarti yang mampu menentang Suharto. Bayang-bayang pembunuhan massal yang dilakukan tentaranya Suharto pada akhir 1965 sampai awal 1966 menciptakan teror tersendiri di dalam benak rakyatnya.
Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap dihancurkan oleh Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee, eksploitasi yang dilakukan kubu penguasa terhadap rakyat kecil. Patut digaris-bawahi jika eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini. Tak aneh jika sekarang ada yang berterus terang jika Suharto adalah gurunya.
Catatan hitam tentang Suharto tidak berhenti sampai disini. Dalam penegakan Hak Asasi manusia (HAM) misalnya, rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri sebagai rezim fasis-militeristis, sebagaimana Jerman di bawah Hitler, Italia di bawah Mussolini, Kamboja di bawah Polpot, dan Chile di bawah Jenderal Augusto Pinochet. Ini ditegaskan Indonesianis asal Perancis, Francois Raillon. Bahkan M.C.
Ricklefs, sejarawan Australia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda. “Orde Baru lebih banyak melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” tegas Ricklefs yang bertahun-tahun menelusuri sejarah bangsa ini sejak zaman masuknya Islam.
Dalam tulisan selanjutnya akan dipaparkan satu-persatu “prestasi” rezim Suharto dalam penegakan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut umat Islam, hubungan haramnya dengan Zionis-Israel, dan banyak lagi yang lainnya.(bersambung/rd)






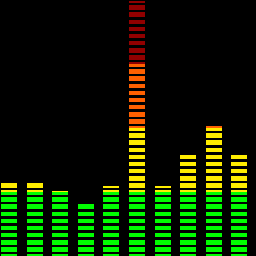









0 komentar:
Posting Komentar